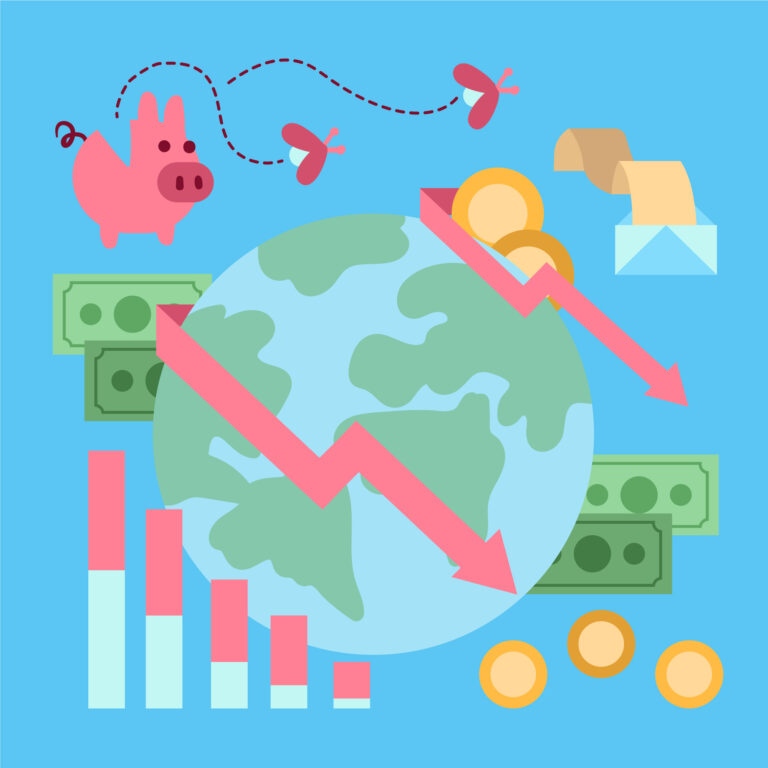Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makro seperti kebijakan nasional, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga oleh peran aktif pemerintah daerah dalam merancang dan menjalankan berbagai program pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah-baik provinsi, kabupaten, maupun kota-memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui kebijakan fiskal, penerbitan regulasi, pembangunan infrastruktur, hingga fasilitasi investasi dan pemberdayaan masyarakat. Artikel ini menguraikan secara mendalam berbagai peran strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan penjelasan yang terang dan mudah dipahami bagi masyarakat awam.
1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat daerah tidak mungkin tercapai tanpa adanya perencanaan pembangunan yang terstruktur, komprehensif, dan berbasis data serta aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi panduan utama pembangunan selama lima tahun. Dokumen ini tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi acuan strategis yang menyatukan visi dan misi kepala daerah dengan arah pembangunan nasional serta kondisi riil lapangan. Setiap tahun, RPJMD ini diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebuah dokumen teknis yang memuat prioritas tahunan, pagu indikatif anggaran, serta program/kegiatan unggulan yang diarahkan untuk mendongkrak sektor-sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara konkret.
1.1. Analisis Potensi Lokal
Langkah awal yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah memahami karakteristik ekonomi lokal secara menyeluruh. Pemerintah daerah wajib melakukan pemetaan potensi wilayah, baik yang bersifat sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, kehutanan, maupun potensi sektor jasa dan pariwisata. Proses ini tidak hanya berbasis pada data statistik dari BPS, tetapi juga diperkuat dengan observasi lapangan, dialog dengan pelaku usaha lokal, serta konsultasi dengan tokoh masyarakat. Misalnya, di daerah dataran tinggi dengan produksi hortikultura yang besar, prioritas anggaran diarahkan untuk pengembangan irigasi tetes, pelatihan petani milenial, dan pembangunan cold storage. Di sisi lain, daerah pesisir dengan potensi wisata bahari akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dermaga, pelatihan homestay, dan promosi destinasi digital. Dengan cara ini, anggaran tidak disebar secara merata, melainkan difokuskan pada sektor yang paling menjanjikan dampak ekonomi jangka panjang.
1.2. Forum Musrenbang yang Inklusif
Perencanaan yang baik juga harus bersifat partisipatif agar pembangunan tidak menjadi agenda sepihak dari pemerintah. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan ide-ide mereka secara langsung. Dimulai dari Musrenbang desa atau kelurahan, proses ini berjenjang ke tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota, dengan partisipasi beragam kelompok: petani, pedagang, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, hingga komunitas adat. Musrenbang tidak hanya bertujuan menjaring usulan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah yang aktif membina dan mendokumentasikan proses ini akan mendapatkan peta kebutuhan masyarakat yang lebih tajam, sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan anggaran yang akan diambil.
2. Kebijakan Fiskal dan Insentif Investasi
Di tengah keterbatasan fiskal nasional, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan kapasitas fiskalnya sendiri melalui kebijakan pajak dan retribusi yang adil serta pemberian insentif bagi pelaku usaha. Pendekatan ini penting karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga pada dinamika investasi swasta dan aktivitas sektor produktif. Oleh karena itu, strategi fiskal yang diterapkan pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlindungan terhadap iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
2.1. Pengelolaan Pajak Daerah
Pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola pajak-pajak tertentu, seperti Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, strategi fiskal bukan hanya tentang menaikkan tarif, melainkan memperluas basis pajak melalui digitalisasi pelayanan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan kampanye literasi pajak kepada pelaku UMKM. Dengan sistem perpajakan yang transparan dan efisien-misalnya melalui e-SPTPD (pelaporan pajak online) dan QRIS untuk pembayaran-PAD bisa meningkat tanpa membebani masyarakat. Bahkan, melalui insentif pajak sementara (tax break), daerah dapat mendorong tumbuhnya sektor baru seperti industri kreatif dan ekonomi digital.
2.2. Insentif Investasi Lokal
Investasi adalah mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi, dan dalam konteks daerah, peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan ekosistem investasi yang ramah dan menjanjikan. Pemerintah daerah dapat menawarkan insentif dalam bentuk kemudahan perizinan, penyediaan lahan siap bangun (land banking), serta pemberian fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif pajak lokal atau pembebasan retribusi. Semua proses ini dilakukan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission). Di beberapa daerah, pemerintah bahkan membuat perjanjian kinerja dengan investor-jika target serapan tenaga kerja lokal terpenuhi, maka insentif diperpanjang. Kebijakan semacam ini menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan: pengusaha mendapatkan kepastian usaha, masyarakat memperoleh lapangan kerja, dan pemerintah meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi riil.
3. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa infrastruktur yang memadai. Akses jalan yang lancar, jaringan logistik yang efisien, pasar tradisional yang tertata, serta fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman adalah prasyarat bagi kegiatan ekonomi untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah daerah, melalui APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, memiliki kewajiban merancang dan membangun infrastruktur yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3.1. Jalan dan Transportasi Publik
Jalan merupakan urat nadi ekonomi daerah, dan pembangunan maupun perbaikannya memiliki efek berganda yang besar terhadap produktivitas. Pemerintah daerah secara rutin mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, hingga jalan lingkungan yang menghubungkan sentra produksi ke pasar. Tidak hanya itu, sistem transportasi publik juga menjadi perhatian utama, terutama di kota-kota dengan kepadatan tinggi. Pengadaan bus sekolah, angkutan kota yang terintegrasi, dan fasilitas halte yang ramah disabilitas tidak hanya mempermudah mobilitas warga tetapi juga mengurangi beban biaya transportasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli dan produktivitas tenaga kerja.
3.2. Pasar Rakyat dan Fasilitas Logistik
Pasar rakyat merupakan jantung dari ekonomi lokal, tempat bertemunya produsen, pedagang, dan konsumen. Oleh karena itu, revitalisasi pasar tradisional menjadi salah satu strategi kunci pemerintah daerah untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pembangunan pasar tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek manajemen, sanitasi, keamanan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat pengolahan hasil pertanian (TPHP), gudang logistik, dan cold storage sangat diperlukan untuk memperpanjang masa simpan produk, mengurangi food loss, dan meningkatkan daya tawar petani dan nelayan. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan BUMDes atau koperasi untuk mengelola logistik secara efisien, sehingga rantai distribusi lebih pendek dan harga di tingkat petani menjadi lebih kompetitif.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam membangun infrastruktur fisik seperti jalan dan pasar, tetapi juga dalam membentuk manusia-manusia yang kompeten, sehat, dan produktif. SDM yang unggul akan menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing, wirausaha yang inovatif, serta masyarakat yang berdaya dalam menghadapi tantangan ekonomi masa kini dan masa depan.
4.1. Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah daerah secara aktif menjalin kemitraan dengan sekolah kejuruan, balai latihan kerja, dan perguruan tinggi vokasi dalam rangka menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kurikulum pelatihan didesain agar selaras dengan kebutuhan pasar, baik itu di sektor manufaktur, pertanian modern, pariwisata, maupun ekonomi digital. Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi ini mencakup pelatihan teknis, soft skill seperti manajemen waktu dan kerja tim, hingga penguasaan teknologi informasi. Selain itu, banyak daerah mulai mendorong model dual system seperti di negara maju-yakni siswa belajar di sekolah sambil magang di perusahaan lokal-sehingga ketika lulus, mereka tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga pengalaman kerja nyata.
4.2. Kewirausahaan dan UMKM
Di tengah tantangan terbatasnya lapangan kerja formal, pemerintah daerah mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Berbagai program disiapkan untuk mendukung wirausaha lokal, mulai dari pelatihan literasi keuangan, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), BUMDes, koperasi, atau lembaga keuangan mikro lainnya. Program inkubasi bisnis yang melibatkan perguruan tinggi dan asosiasi pengusaha juga dikembangkan di beberapa daerah, di mana pelaku UMKM dibimbing mulai dari perencanaan usaha, produksi, pengemasan, pemasaran, hingga digitalisasi melalui pelatihan digital marketing dan penggunaan e-commerce. Semua ini bertujuan untuk menciptakan UMKM yang mandiri, berorientasi pasar, dan mampu naik kelas.
5. Fasilitasi Iklim Usaha dan Kemudahan Berusaha
Selain menyiapkan SDM yang kompeten, pemerintah daerah juga memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tanpa adanya lingkungan usaha yang nyaman, aman, dan efisien, pelaku usaha akan enggan berinvestasi, dan ekonomi daerah pun akan stagnan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi menjadi instrumen penting yang harus terus digalakkan di tingkat daerah.
5.1. Layanan Satu Pintu
Salah satu terobosan penting yang kini diterapkan di banyak daerah adalah pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP), sebuah pusat layanan terpadu di mana masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan dalam satu lokasi. Dengan menggabungkan berbagai instansi, baik dari tingkat kabupaten/kota maupun pusat, MPP mempersingkat waktu pelayanan yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari, bahkan jam. Selain itu, sistem perizinan online berbasis Online Single Submission (OSS) juga diintegrasikan di tingkat daerah, memungkinkan pelaku usaha mendaftar secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor. Ini memberikan kepastian hukum, menekan biaya usaha, dan meningkatkan daya tarik investasi daerah.
5.2. Regulasi Ringan dan Proteksi Konsumen
Selain menyederhanakan perizinan, pemerintah daerah juga harus menciptakan peraturan daerah (Perda) yang tidak membebani pelaku usaha kecil. Banyak daerah yang menerapkan Perda yang adaptif-misalnya, membebaskan retribusi bagi usaha pemula selama dua tahun pertama atau memberikan insentif pajak kepada usaha ramah lingkungan. Namun di sisi lain, pengawasan terhadap kualitas produk dan layanan tetap harus dilakukan melalui perlindungan konsumen yang kuat. Dengan adanya pengawasan yang adil dan tegas, masyarakat merasa aman saat bertransaksi, sementara pelaku usaha memperoleh kepastian regulasi dan persaingan yang sehat.
6. Promosi dan Pemasaran Daerah
Agar produk unggulan daerah, potensi pariwisata, dan peluang investasi dikenal luas oleh masyarakat nasional maupun global, pemerintah daerah harus aktif melakukan promosi melalui berbagai saluran. Promosi yang dilakukan dengan strategi yang tepat bukan hanya mendongkrak citra positif daerah, tetapi juga mampu mendatangkan arus investasi dan kunjungan wisata yang signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja.
6.1. Branding Daerah
Branding daerah bukan hanya sekadar membuat logo atau slogan, tetapi juga menciptakan identitas yang membedakan daerah tersebut dari daerah lain. Misalnya, sebuah kabupaten pertanian bisa mengangkat identitas sebagai “Lumbung Hortikultura Indonesia”, sementara kota berbasis jasa bisa menonjolkan dirinya sebagai “Kota Seribu Layanan Digital”. Branding ini diperkuat dengan peluncuran kalender event tahunan, festival budaya, lomba-lomba nasional, hingga forum bisnis daerah. Identitas daerah yang kuat memudahkan masyarakat luas untuk mengingat, mengenali, dan merasa tertarik untuk berinteraksi dengan daerah tersebut, baik sebagai konsumen produk lokal, wisatawan, maupun investor.
6.2. Pameran dan Bazar
Keikutsertaan daerah dalam pameran nasional dan internasional juga menjadi strategi penting dalam membuka pasar baru. Pemerintah daerah biasanya memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti expo, baik di dalam negeri seperti Inacraft, Trade Expo Indonesia, maupun pameran dagang luar negeri seperti di Singapura, Jepang, atau Eropa. Tidak hanya itu, daerah juga menyelenggarakan bazar atau festival ekonomi lokal di tingkat regional, yang tidak hanya memasarkan produk, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha, pembeli, investor, dan mitra logistik. Pemerintah biasanya menyediakan booth gratis, melatih pelaku UMKM dalam menyiapkan materi promosi, serta membantu mengurus sertifikasi halal dan BPOM agar produk bisa diterima di pasar yang lebih luas.
7. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis
Dalam membangun ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan kebutuhan sumber daya yang besar menuntut adanya kolaborasi lintas sektor yang sistematis dan strategis. Oleh karena itu, kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting yang harus terus diperkuat agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan berdampak nyata di lapangan.
7.1. Kemitraan Akademisi-Usaha
Universitas dan lembaga riset di daerah memiliki potensi besar sebagai mitra pembangunan ekonomi, terutama dalam memberikan kajian ilmiah, mengembangkan inovasi teknologi, serta menciptakan tenaga kerja siap pakai. Pemerintah daerah dapat menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membentuk innovation hub atau pusat unggulan inovasi daerah yang memfokuskan riset pada pengembangan produk unggulan lokal-misalnya riset benih unggul untuk pertanian, teknologi pengolahan hasil laut, atau pengemasan produk UMKM. Dalam kemitraan ini, dunia usaha juga dapat berperan sebagai pengguna dan penyandang dana riset terapan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pemberi insentif. Hasilnya adalah sebuah ekosistem inovasi yang saling menguntungkan, di mana akademisi menghasilkan solusi nyata, dunia usaha mendapatkan nilai tambah, dan masyarakat menikmati produk yang berkualitas dan terjangkau.
7.2. Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Swasta
Di sisi lain, peran pemerintah pusat dan sektor swasta tidak kalah penting. Program nasional seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program padat karya tunai dari kementerian dapat disinergikan oleh pemerintah daerah dengan program lokal untuk memperbesar dampaknya. Misalnya, pembangunan irigasi kecil melalui dana pusat bisa didukung pelatihan petani oleh dinas pertanian kabupaten. Sementara itu, perusahaan swasta yang beroperasi di daerah diharapkan tidak hanya fokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga terlibat aktif dalam pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah daerah bisa menyusun CSR mapping agar program tanggung jawab sosial perusahaan terarah sesuai prioritas pembangunan lokal, seperti peningkatan akses air bersih, pendidikan vokasi, atau pelatihan UMKM.
8. Digitalisasi Layanan dan Ekonomi Digital
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat bekerja, berusaha, dan berinteraksi. Pemerintah daerah yang cerdas dan adaptif perlu memanfaatkan peluang digitalisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga untuk membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi dan konektivitas digital.
8.1. E-Government dan Layanan Publik Digital
Digitalisasi layanan publik adalah langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang bersih, cepat, dan transparan. Pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem e-government mampu memberikan pelayanan perizinan, informasi investasi, hingga pembayaran pajak secara daring, tanpa harus menunggu antrean panjang di kantor-kantor pelayanan. Sistem seperti ini memotong birokrasi yang rumit, mengurangi potensi korupsi, dan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha. Contohnya, sistem perizinan terpadu berbasis Online Single Submission (OSS) kini mulai terintegrasi dengan platform daerah, memungkinkan pelaku UMKM mengurus izin usaha hanya dalam hitungan jam. Tidak hanya itu, informasi tentang peluang investasi, lahan industri, dan insentif daerah juga dapat dipublikasikan secara interaktif melalui dashboard investasi yang bisa diakses calon investor dari mana saja.
8.2. Peningkatan Ekonomi Digital Lokal
Selain reformasi layanan, pemerintah daerah juga perlu mendorong warganya untuk aktif dalam ekonomi digital. UMKM lokal harus dibekali kemampuan digital marketing, penggunaan media sosial untuk promosi, hingga akses ke marketplace nasional dan global seperti Tokopedia, Shopee, hingga Amazon. Beberapa daerah bahkan sudah mulai membangun platform e-commerce daerah yang mempertemukan produsen lokal dengan konsumen, serta menyediakan fulfillment center atau pusat logistik terpadu untuk memudahkan pengiriman. Tidak hanya itu, dukungan terhadap perusahaan rintisan (startup) berbasis digital juga perlu diperkuat dengan membangun co-working space, program akselerator bisnis, serta akses pembiayaan dari investor lokal maupun nasional. Di sektor keuangan, kehadiran fintech atau teknologi keuangan seperti e-wallet dan peer-to-peer lending semakin mempermudah pelaku usaha kecil mendapatkan modal usaha tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional.
9. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang jelas agar setiap program yang dirancang benar-benar menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang efektif harus mampu membaca data, mengukur capaian, serta melakukan perbaikan kebijakan secara terus-menerus berdasarkan evaluasi yang obyektif dan terbuka.
9.1. Indikator Kinerja Utama
Pemerintah daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan relevan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Misalnya, indikator pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, laju inflasi, dan indeks kemudahan berusaha menjadi tolok ukur yang wajib dianalisis secara berkala. Selain indikator makro, indikator mikro seperti jumlah UMKM aktif, jumlah izin usaha yang terbit, atau nilai ekspor produk lokal juga penting dipantau sebagai cermin dinamika ekonomi riil di lapangan. IKU ini kemudian menjadi dasar penilaian kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta bahan evaluasi dalam sidang paripurna DPRD maupun audit kinerja oleh lembaga pengawas.
9.2. Forum Evaluasi Publik
Partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam mengevaluasi pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemerintah daerah bisa menyelenggarakan forum evaluasi publik atau dialog pembangunan yang mempertemukan pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Dalam forum ini, masyarakat bisa memberikan masukan, menyampaikan keluhan, bahkan mengusulkan solusi terhadap persoalan pembangunan. Forum semacam ini mendorong transparansi, meningkatkan akuntabilitas publik, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
10. Penutup
Keseluruhan uraian di atas menggambarkan betapa penting dan strategisnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mulai dari tahap perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal, kebijakan fiskal yang ramah usaha, pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas, penguatan SDM dan UMKM, hingga pemanfaatan teknologi digital dan penguatan evaluasi program, semua harus dijalankan secara terpadu dalam satu kesatuan kebijakan daerah yang progresif.
Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah daerah yang memiliki visi ekonomi jangka panjang dan kapasitas eksekusi yang baik akan mampu menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan ekonomi warganya. Dengan dukungan semua pihak-baik masyarakat, swasta, akademisi, dan pusat-pemerintah daerah bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi yang nyata, mendorong pertumbuhan dari pinggiran, memperkecil ketimpangan antarwilayah, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, adil, dan sejahtera dari bawah ke atas.