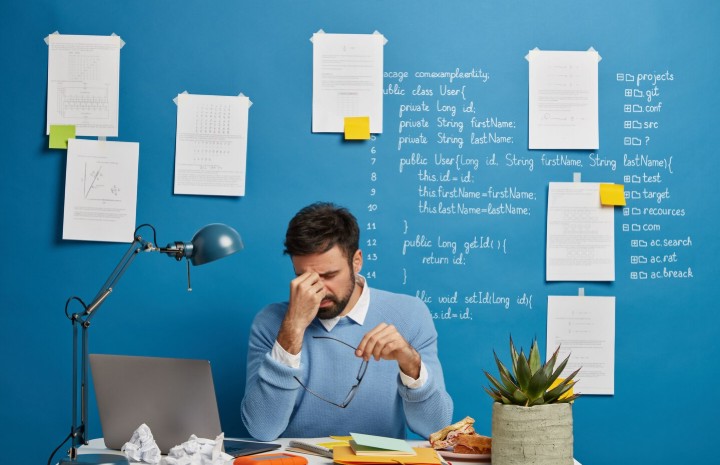Pendahuluan
Integrasi perencanaan dan penganggaran adalah landasan penting untuk tata kelola publik yang efektif. Singkatnya, integrasi ini berarti menyelaraskan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan perencanaan program dengan alokasi anggaran yang realistis serta mekanisme pengukuran kinerja. Tujuannya: memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan, meningkatkan efektivitas layanan, dan meminimalkan pemborosan atau kegiatan yang tidak berdampak.
Di banyak organisasi publik, perencanaan dan anggaran masih berjalan terpisah-perencanaan menghasilkan daftar program ambisius sementara anggaran dibuat berdasarkan kebiasaan historis atau tekanan politis. Akibatnya, ada gap antara apa yang direncanakan dan apa yang didanai; indikator kinerja kabur; serta akuntabilitas menjadi lemah. Era digital, keterbukaan data, dan tuntutan akuntabilitas publik menuntut model integrasi yang lebih modern: berbasis kinerja, didukung data, dan responsif terhadap perubahan lingkungan.
Artikel ini membahas secara rinci prinsip, tantangan, metode, praktik teknologi, kapasitas organisasi, partisipasi publik, dan roadmap implementasi integrasi perencanaan-penganggaran. Setiap bagian disusun agar mudah dipahami dan langsung dapat dijadikan referensi praktis untuk pembuat kebijakan, manajer keuangan, perencana, auditor, dan aktor masyarakat sipil. Dengan pendekatan ini diharapkan pembaca memperoleh peta jalan konkret: bagaimana mentransformasi proses birokratis menjadi sistem tata kelola yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil.
1. Konsep dasar dan urgensi integrasi perencanaan-penganggaran
Integrasi perencanaan dan penganggaran bukan sekadar prosedur administratif; ia adalah proses strategis yang menghubungkan tujuan pembangunan dengan sumber daya finansial dan mekanisme pengukuran hasil. Konsep ini muncul dari kebutuhan agar kebijakan publik tidak berhenti pada dokumen rencana yang indah, melainkan terealisasi melalui alokasi anggaran yang selaras. Ada beberapa elemen kunci dalam konsep integrasi:
- Keselarasan tujuan-anggaran-indikator: setiap program atau kegiatan harus punya tujuan jelas (outcome), indikator terukur, target waktu, serta alokasi anggaran yang memadai. Ini mencegah terjadinya “anggaran untuk kegiatan” tanpa efek nyata pada sasaran strategis.
- Siklus yang sinkron: perencanaan strategis (mis. RPJMD/RPJMN), rencana kerja tahunan (RKT/RKPD), dan siklus anggaran (APBD/APBN) harus saling terkait dalam timeline yang memungkinkan verifikasi dan rekalibrasi. Keterlambatan satu bagian akan merusak keseluruhan siklus.
- Performance-based budgeting (PBB): pendekatan yang mengaitkan pendanaan dengan kinerja-baik input, output, maupun outcome-memaksa unit kerja untuk berorientasi pada hasil. PBB dapat berbentuk anggaran berbasis program, anggaran berbasis kinerja, atau penggunaan multi-year budgeting untuk capex.
Urgensi integrasi muncul dari beberapa tekanan nyata:
- Keterbatasan sumber daya: anggaran publik selalu terbatas; tanpa prioritisasi yang jelas, dana tersebar tipis dan dampak menjadi minim.
- Tuntutan akuntabilitas publik: warga, DPR, dan donor menuntut bukti bahwa belanja publik menghasilkan hasil nyata.
- Kebutuhan responsif: krisis (pandemi, bencana) menuntut anggaran yang fleksibel dan mampu dialihkan ke prioritas emergent; integrasi mempermudah realokasi berbasis data.
- Efisiensi administrasi: meminimalkan duplikasi program antar-OPD dan mendorong sinergi lintas sektor.
Manfaat praktis integrasi: pengambilan keputusan yang berbasis bukti, pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan mekanisme monitoring & evaluation (M&E). Namun, integrasi bukan otomatis; perlu desain kebijakan, perubahan proses, teknologi, dan budaya organisasi agar sinergi antara perencanaan dan anggaran benar-benar bekerja.
2. Hambatan umum: silo organisasi, timing, dan kualitas data
Walau konsep integrasi jelas, penerapan di lapangan sering buntu akibat hambatan struktural dan kultural. Memahami hambatan ini penting agar desain reformasi bisa spesifik dan efektif.
Silo organisasi: OPD bekerja berdiri sendiri, dengan target dan indikator yang sering tumpang tindih atau tidak selaras. Silo ini muncul karena struktur birokrasi tradisional-tanggung jawab didefinisikan vertikal-membuat koordinasi antar unit menjadi sulit. Akibatnya muncul duplikasi belanja, kontradiksi kebijakan, dan peluang inefisiensi.
Timing yang mismatch: perencanaan strategis sering disusun jauh sebelum siklus anggaran; sedangkan penyusunan anggaran mengikuti timeline yang berbeda. Misalnya perencanaan jangka menengah selesai setelah penetapan kebijakan anggaran; ini menyebabkan target strategis tidak sempat diterjemahkan ke dalam anggaran tahunan.
Kualitas data yang buruk: integrasi membutuhkan data andal-baseline, indikator, realisasi anggaran, dan outcome. Namun seringkali data tidak lengkap, terlambat diupdate, atau tidak standar (beragam unit, format, dan definisi). Ketidakkonsistenan ini membuat pengukuran kinerja tidak valid.
Ketiadaan mekanisme tracking dan M&E: tanpa sistem monitoring yang terotomasi, verifikasi capaian mengandalkan laporan manual yang rentan manipulasi dan keterlambatan. Evaluasi sering dilakukan setelah periode selesai sehingga tidak memberi ruang untuk perbaikan di tengah jalan.
Kekurangan kapasitas SDM: perencana dan bendahara mungkin tidak memiliki keterampilan analitik, pengetahuan tentang PBB, atau kemampuan teknis untuk mengoperasikan sistem integrasi digital. Rotasi pegawai dan low institutional memory memperparah kondisi.
Resistensi terhadap perubahan: birokrasi kerap nyaman dengan rutinitas; reformasi yang mengubah alur tugas dan membuka transparansi dapat bertemu penolakan, khususnya bila mengancam praktik informal.
Ketergantungan politik: alokasi anggaran sering dipengaruhi kepentingan politik dan lobbying sehingga prioritas teknis tersingkir.
Solusi mitigasi:
- Bentuk cross-functional teams dan mekanisme koordinasi terjadwal (budgeting roundtables).
- Sinkronkan timeline perencanaan dan anggaran lewat peraturan internal.
- Bangun data governance: standar indikator, data catalog, dan quality checks.
- Investasi M&E dan dashboard real-time.
- Program capacity building berkelanjutan untuk perencana dan akuntan.
- Kebijakan change management dan insentif kinerja untuk mendorong adopsi.
Menangani hambatan ini memerlukan pendekatan holistik: teknis, institusional, dan politis. Tanpa itu integrasi tetap menjadi jargon alih-alih praktik operasi.
3. Kerangka kebijakan dan regulasi pendukung integrasi
Agar integrasi perencanaan-penganggaran berjalan, diperlukan payung kebijakan yang jelas-baik di level nasional maupun organisasi-yang mengatur peran, timeline, standar, dan mekanisme akuntabilitas. Kerangka ini memastikan kesinambungan dan legitimasi proses.
Standar nasional dan instruksi kepemimpinan: pemerintahan pusat biasanya menerbitkan pedoman perencanaan dan penganggaran (mis. peraturan menteri, PMK/Permendagri). Instruksi pimpinan (kepala daerah/menteri) yang menegaskan prioritas strategis dan mewajibkan penggunaan tool tertentu (mis. e-planning, e-budgeting) memperkuat implementasi.
Regulasi timeline sinkron: aturan yang mensyaratkan sinkronisasi dokumen strategis (RPJMD/RPJMN) dengan medium-term expenditure framework (MTEF) dan APBD/APBN memaksa unit kerja untuk merencanakan sesuai dengan siklus anggaran. Batas waktu pengajuan rencana, verifikasi, dan revisi harus diatur.
Mandatory performance frameworks: menetapkan bahwa anggaran harus disusun berdasarkan program dan indikator kinerja (output/outcome) mempromosikan PBB. Regulasi dapat mengatur format dokumen-logframe, indicators, baselines, targets, assumptions-sehingga konsistensi terjaga.
Data governance & interoperability rules: standar metadata, nomenklatur akun, dan requirement API untuk sistem keuangan, perencanaan, serta monitoring (LAKIP, e-forms) sangat penting. Regulasi data memuat aspek data ownership, frekuensi update, dan retensi.
Sanksi dan mekanisme audit: adanya mekanisme audit internal dan eksternal (BPK, Inspektorat) untuk memeriksa kesesuaian anggaran dengan rencana dan kualitas pencapaian. Sanksi tegas terhadap manipulasi data atau penyimpangan anggaran meningkatkan efek kepatuhan.
Pengaturan partisipasi publik: peraturan yang mensyaratkan publikasi rencana anggaran dan peluang partisipasi (musrenbang, consultative budgeting) memperluas checks and balances serta legitimasi.
Fleksibilitas untuk contingency: kerangka harus mengakomodasi fleksibilitas anggaran dalam situasi darurat (pandemi, bencana) dengan prosedur cepat namun transparan untuk realokasi.
Harmonisasi pusat-daerah: aturan yang memetakan kewenangan dan alokasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah mengurangi tumpang tindih dan konflik peran. Mekanisme equalization or conditional grants dapat diarahkan ke prioritas nasional yang selaras dengan kebutuhan daerah.
Implementasi kerangka regulasi memerlukan capacity building untuk memahami ketentuan dan system support agar pelaksanaan bersifat mekanis, bukan sekedar formalitas. Regulasi bagus tanpa kapasitas dan political will sama-sama tidak efektif.
4. Metodologi anggaran berbasis kinerja dan instrumen pendanaan
Untuk menjembatani rencana dan anggaran, banyak pemerintah mengadopsi metodologi anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting, PBB) dan instrumen seperti Medium-Term Expenditure Framework (MTEF), Program Budgeting, atau Output-Based Budgeting. Masing-masing menawarkan cara berbeda untuk memprioritaskan pengeluaran.
Performance-Based Budgeting (PBB)
Inti PBB adalah pengaitan alokasi anggaran dengan hasil yang diharapkan. Anggaran diorganisasikan berdasarkan program yang memiliki tujuan, indikator, serta target. Keuntungan PBB: memfokuskan pengelola pada outcome, memudahkan evaluasi, dan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.
Medium-Term Expenditure Framework (MTEF)
MTEF adalah mekanisme perencanaan pendanaan multi-tahun (3-5 tahun) yang menyelaraskan kebijakan strategis dengan resource envelope. MTEF membantu perencanaan investasi besar dan menjaga keberlanjutan fiskal-mis. memastikan bahwa komitmen belanja berkelanjutan tidak melebihi kapasitas anggaran.
Program Budgeting & Logical Frameworks
Program budgeting memecah anggaran ke dalam program-logical framework (input→output→outcome) sehingga setiap alokasi mempunyai justifikasi logis. Logframe membantu identifikasi indikator, baseline, dan asumsi.
Output-Based and Results-Based Financing
Untuk beberapa layanan, results-based financing (RBF) atau output-based aid dapat dipakai: pembayaran atau pelepasan dana terikat realtime pada pencapaian indikator (mis. jumlah siswa yang lulus, jumlah vaksinasi). Instrumen ini meningkatkan insentif pada pencapaian hasil.
Instrumen fiskal inovatif
- Conditional transfers: dana pusat ke daerah yang terkait dengan pencapaian program prioritas.
- Performance grants: insentif tambahan bagi OPD yang mencapai target.
- Public-Private Partnership (PPP): untuk proyek infrastruktur, PPP menyelaraskan investasi swasta dengan prioritas publik, namun memerlukan mekanisme pengawasan kontraktual kuat.
Praktik implementasi:
- Definisikan program dan sub-program dengan jelas; kaitkan indikator dan alokasi yang memadai.
- Gunakan MTEF untuk mengelola komitmen multi-year-hindari backlog kewajiban ke depan.
- Rancang sistem payment-by-results untuk area yang mudah diukur; gunakan escrow atau performance bond untuk pengadaan besar.
- Pantau perverse incentives: pastikan indikator tidak mendorong manipulasi (mis. hanya mengejar jumlah tanpa kualitas).
- Integrasikan dengan sistem akuntansi-cocokkan chart of accounts agar realisasi bisa dibandingkan dengan anggaran program.
Metode ini menuntut kemampuan analytical dan data yang kuat, serta perubahan budaya pengelolaan dari input-centric ke outcome-oriented. Dengan desain yang matang, PBB dan MTEF menambah kredibilitas dan efektivitas anggaran publik.
5. Peran data dan sistem informasi: e-planning, e-budgeting, dan dashboard kinerja
Teknologi informasi menjadi enabler utama integrasi perencanaan dan penganggaran. Sistem digital mempercepat aliran data, memberikan transparansi, dan mendukung analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.
e-Planning dan e-Budgeting
Platform e-planning memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan secara kolaboratif-mengumpulkan masukan, memvalidasi rencana program, dan menyelaraskan prioritas antar-unit. e-Budgeting memungkinkan pembuatan anggaran berbasis program dengan workflow persetujuan, penelusuran perubahan, dan integrasi ke sistem keuangan (treasury).
Dashboard kinerja
Dashboard interaktif menyajikan indikator kunci (KPI), realisasi anggaran, dan trend waktu nyata. Dashboard dapat disesuaikan untuk level pemimpin (high-level KPIs), manajer OPD (output & process indicators), dan publik (transparency portal).
Integrasi sistem & interoperability
Kunci teknis: API-first architecture-sistem perencanaan, keuangan, pengadaan, HR, dan M&E harus saling terhubung sehingga data mengalir otomatis, mengurangi copy-paste manual. Data warehouse atau semantic layer (facts & dimensions) menyederhanakan query KPI lintas sistem.
Data governance & master data
Untuk integrasi yang valid, perlu master data management (unit organisasi, program codes, account codes). Metadata catalog memuat definisi indikator, sumber data, frekuensi update, dan owner-membantu traceability dan audit.
Analytics & early-warning systems
Dengan analytics engine, pemerintah dapat melakukan: anomaly detection (penurunan capaian mendadak), forecasting (proyeksi realisasi anggaran), dan scenario modeling (dampak reallocation). Early-warning alerts membantu pengambilan tindakan korektif lebih cepat.
Keamanan & akses kontrol
Sistem harus memiliki IAM, role-based access, enkripsi, dan audit logs. Untuk portal publik, data harus di-aggregate atau di-anonimkan agar tidak melanggar privasi.
Praktik implementasi:
- Mulai dengan pilot: integrasi 2-3 sistem kunci dan 5-10 KPI priority.
- Kembangkan data catalog sebelum build dashboard agar definisi KPI konsisten.
- Investasi pada UX: dashboard harus mudah dibaca, mobile-friendly, dan dilengkapi drill-down.
- Bangun team data ops / M&E yang menjaga kualitas data dan menyajikan insight rutin.
Teknologi tidak menggantikan kebijakan; ia memperbesar efektivitas apabila didampingi tata kelola data yang kuat, kapasitas analitik, dan komitmen kepemimpinan untuk menggunakan data dalam pengambilan keputusan.
6. SDM, budaya kinerja, dan manajemen perubahan
Integrasi tak akan bertahan tanpa SDM dan budaya organisasi yang mendukung. Penguatan kapasitas, perubahan mindset, dan manajemen resistensi menjadi komponen krusial.
Kebutuhan kapabilitas:
- Data literacy: pegawai harus mampu membaca dashboard, menginterpretasi KPI, dan membuat rekomendasi berbasis data.
- Perencanaan & anggaran berbasis hasil: pelatihan pada logframe, desain indikator, kosting program.
- Technical skills: penggunaan e-planning, e-budgeting, serta dasar analytics.
- Soft skills: collaboration, stakeholder engagement, dan komunikasi perubahan.
Budaya kinerja:
- Leadership by example: pimpinan menggunakan dashboard dalam rapat, meminta evidence-based briefings, dan menetapkan target yang jelas.
- Freedom to experiment: beri ruang untuk pilot dan perbaikan tanpa hukuman atas kegagalan selama proses pembelajaran.
- Reward & accountability: hubungkan appraisal dan insentif dengan pencapaian outcome, bukan sekadar penyelesaian dokumen.
Change management:
- Stakeholder mapping & engagement: identifikasi aktor kunci (pimpinan, finance, OPD, DPR, publik) dan rancang strategi komunikasi.
- Quick wins: capai hasil awal yang bisa ditunjukkan (mis. dashboard untuk 3 KPI utama) agar membangun dukungan.
- Training & mentoring: gabungkan pelatihan formal dengan mentoring on-the-job. Sertifikasi internal dapat membantu profesionalisasi.
- Institutionalize processes: SOP baru untuk perencanaan-anggaran yang terdokumentasi; rutinitas review berkala (monthly/quarterly).
- Monitoring change: metrik adopsi sistem, kualitas data, dan frekuensi penggunaan dashboard menjadi indikator keberhasilan transformasi.
Mengatasi resistensi:
- Komunikasikan manfaat (mengurangi pekerjaan administratif, mempercepat keputusan).
- Libatkan early adopters sebagai champion.
- Tawarkan dukungan teknis langsung (helpdesk) dan materi pelatihan modular.
Sustainability of skills:
- Program rotasi dan knowledge transfer sehingga pengetahuan tidak hilang saat pegawai pindah.
- Kerja sama dengan akademia dan lembaga pelatihan untuk pipeline talenta.
Budaya kinerja yang berkelanjutan membutuhkan leadership, pelatihan berkelanjutan, dan mekanisme reward yang selaras. Ketika SDM menyadari manfaat praktis integrasi, adopsi menjadi lebih cepat dan reformasi lebih tahan lama.
7. Partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas
Integrasi perencanaan-penganggaran yang baik harus melibatkan publik. Partisipasi dan transparansi memperkaya kualitas rencana serta menambah legitimasi alokasi anggaran.
Mengapa partisipasi penting:
- Memastikan rencana responsif terhadap kebutuhan masyarakat; indikator outcome lebih relevan.
- Meningkatkan deteksi potensi penyimpangan karena masyarakat dapat memantau realisasi.
- Membangun akuntabilitas politik-wakil rakyat dan eksekutif dipaksa menjelaskan pilihan prioritas.
Model partisipasi:
- Musrenbang dan public hearings: forum tradisional untuk input perencanaan. Namun perlu modernisasi agar inklusif-gunakan mekanisme online, surveys, dan konsultasi khusus untuk kelompok rentan.
- Participatory budgeting (PB): sebagian anggaran dialokasikan melalui proses partisipatif di tingkat lokal; PB meningkatkan kepemilikan masyarakat atas proyek.
- Open data portals: publikasi rencana, alokasi, kontrak, dan realisasi anggaran secara machine-readable (OCDS) memudahkan analisis oleh CSO dan media.
Transparansi yang efektif:
- Data harus berkualitas: lengkap, timely, standardized.
- Visualisasi user-friendly: peta proyek, status realisasi, dan laporan capaian berbasis KPI memudahkan publik.
- Mekanisme pengaduan & feedback: setiap warga bisa melaporkan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai; laporan ditindaklanjuti dan dipublikasikan hasilnya.
Peran media & CSO:
- Jurnalisme data dan CSO dapat men-interpretasi data besar menjadi narasi yang dipahami publik; mereka berfungsi sebagai pengawas eksternal.
- Capacity building CSO dan komunitas meningkatkan kemampuan analisis lokal.
Risiko & mitigasi:
- Data misuse & misinterpretation: edukasi publik diperlukan agar kesimpulan yang ditarik berbasis fakta.
- Security & privacy: pastikan data yang dipublikasikan tidak mengungkap data sensitif individu.
- Tokenism: partisipasi hanya simbolik; harus ada jaminan bahwa masukan publik dipertimbangkan dalam keputusan akhir.
Indikator keberhasilan partisipasi:
- Jumlah masukan publik yang diproses dan mengubah keputusan.
- Frekuensi dan kualitas transparansi publik portal.
- Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap respons pemerintah.
Partisipasi publik bukan beban tambahan-ia meningkatkan kualitas keputusan dan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya ke intervensi yang benar-benar dibutuhkan.
8. Roadmap implementasi dan praktik terbaik: langkah-langkah konkret
Agar integrasi perencanaan-penganggaran bukan hanya konsep, diperlukan roadmap terstruktur: dari assessment awal hingga scale-up. Berikut langkah konkrit dan praktik terbaik yang dapat diadopsi.
Fase 1 – Readiness & Assessment (0-3 bulan)
- Lakukan diagnostic (gap analysis): data inventory, system inventory, kapasitas SDM, dan governance review.
- Bentuk steering committee lintas fungsi (perencanaan, keuangan, TI, hukum).
- Tentukan priority KPIs dan pilot units.
Fase 2 – Pilot & Quick Wins (3-9 bulan)
- Pilih 1-2 program prioritas; terapkan PBB di sana.
- Deploy dashboard awal (3-5 KPI) dengan data integrated dari 2 sistem.
- Sediakan training intensif untuk pengguna pilot dan dokumentasikan SOP.
Fase 3 – Governance & Capacity Building (9-18 bulan)
- Bentuk Centre of Excellence (CoE) untuk perencanaan-anggaran digital.
- Kembangkan data catalog, master data, dan standard indicator definitions.
- Jalankan sertifikasi internal bagi perencana/bendahara.
Fase 4 – Scale-up & Integration (18-36 bulan)
- Integrasikan e-planning, e-budgeting, treasury, procurement, dan M&E.
- Terapkan MTEF untuk program multi-year dan payment-by-results bila relevan.
- Publikasikan portal transparansi dan buka saluran partisipasi online.
Fase 5 – Advanced analytics & Sustainability (36+ bulan)
- Implement predictive analytics untuk forecasting dan early-warning.
- Kembangkan mekanisme performance incentives dan integrate dengan appraisal system.
- Pastikan budget OPEX untuk pemeliharaan sistem dan training berkelanjutan.
Praktik terbaik:
- Start small, scale fast: pilot terfokus memberikan bukti untuk perluasan.
- User-centered design: libatkan end-users sejak awal agar sistem usable.
- Hybrid deployment: manfaatkan cloud untuk scalability tetapi atur data residency sesuai regulasi.
- Public-private-academic partnerships: universitas membantu analytics; sektor swasta membantu tooling; CSO mendukung partisipasi.
- Continuous monitoring & learning: lakukan evaluasi berkala dan iterasi untuk perbaikan.
Pengukuran keberhasilan:
- Proporsi KPI yang dihitung otomatis.
- Penurunan waktu siklus anggaran dan penyusunan rencana.
- Peningkatan output/outcome program yang selaras dengan prioritas.
- Level partisipasi publik dan penggunaan portal transparansi.
Roadmap harus fleksibel-mengakomodasi konteks lokal dan perubahan prioritas fiskal-namun disiplin dalam eksekusi adalah kunci transformasi yang berhasil.
Kesimpulan
Integrasi perencanaan dan penganggaran bukan sekadar agenda teknis-ia merupakan transformasi sistemik yang memadukan kebijakan, teknologi, kapasitas manusia, dan partisipasi publik. Manfaatnya jelas: alokasi sumber daya yang lebih efisien, keputusan yang berbasis bukti, layanan publik yang lebih responsif, dan akuntabilitas yang meningkat. Namun perjalanan menuju integrasi penuh penuh tantangan: silo organisasi, kualitas data yang buruk, kapasitas SDM yang terbatas, serta hambatan politik dan budaya administrasi.
Kunci keberhasilan adalah pendekatan bertahap dan pragmatis: mulailah dengan pilot prioritas yang menghasilkan quick wins; bangun tata kelola data dan interoperabilitas sistem; profesionalisasikan SDM lewat pelatihan dan sertifikasi; serta buka ruang partisipasi publik yang bermakna. Teknologi seperti e-planning, e-budgeting, dashboard kinerja, dan analytics adalah enabler-bukan solusi tunggal-yang harus dipasangkan dengan kebijakan dan kultur kerja baru.
Akhirnya, integrasi yang sukses membutuhkan komitmen kepemimpinan jangka panjang, pendanaan yang berkelanjutan untuk operasional, dan mekanisme pembelajaran berkelanjutan. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan seksama, integrasi perencanaan dan penganggaran bukan hanya meningkatkan efisiensi birokrasi-ia mengubah cara negara melayani warga, memastikan anggaran publik benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.